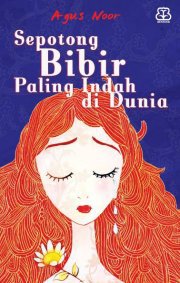Published on RiauPos 03/03/2013,click link below to see
http://www.riaupos.co/spesial.php?act=full&id=1051&kat=2#.UUaRcXrHrMz
Setelah terbelenggu sekian lama, akhirnya katub-katub itu terbuka juga. Apa yang dianggap patut dan tak patut kerananya sudah terbuka. Menjelmalah sebuah dunia banal di mana titik pasti kebenaran itu bisa dipertanyakan dan diperdebatkan. Tak ada lagi singgasana superioritas yang bebas berkuasa mewacanakan segalanya. Apapun yang coba dikokohkan akan selalu ada titik baliknya dan celah untuk meruntuhkannya. Fenomena ini hampir menjalar ke segala penjuru lintas persoalan. Politik, ideologi, ekonomi, sosial, seni, budaya telah terecoki dalam kenihilan kemapanan.
Hal ini tentunya juga merambah ke sastra sebagai salah satu bidang seni. Berawal dari gerakan poststrukturalist, postmodernist dan post-post lainnya, terbitlah lembaran baru di mana setiap karya berhak merayakan pemikirannya tanpa batas dan dikotomi posisi biner. Apa yang adiluhung, avant garde, aufklarung, sublim dan santun bukanlah menjadi suatu pasak mati dan tolok ukur. Sekarang setiap pengarang telah berhak mengusung setiap pergumulan ideologinya, apakah itu hitam, putih, abu-abu. Kiri, kanan, ataupun poros tengah.
Sastra Indonesia sendiri cukup lama juga terbelenggu dari katub-katub budaya yang mengidentikkan diri dengan ketimuran. Timur yang yang pasif dan menjaga hal-hal yang dikotakkan sebagi tabu. Mengenai masalah tabu ini, seks merupakan hal yang dominan dalam wacananya. Dalam ruang sastra sendiri apabila bergumulan dengan seks, maka itu akan dianggap tidak patut untuk budaya kita yang ‘timur’. Maka apabila ada karya seperti ini akan dicap sebagai karya seronok dan jorok, meskipun setiap manusia ingin melakukannya. Akan tetapi karya itu tetap beredar dan pengarangnya memang harus berani dan rela dicap sebagai pengarang murahan yang hanya pandai mengumbar seksual.
Seiring dengan pengaruh pemikiran segala post-post di atas dan reformasi yang juga patut dianggap sebagai titik tolak, para pengarang Indonesia telah berani membungkus tema seks dengan kedalaman yang lebih dan tak hanya mengumbar seksual, meskipun stigma masyarakat masih menilai dengan sama seperti sebelumnya. Nama Ayu Utami bisa jadi sebagai pionir dalam menawarkan citarasa dengan bumbu seksual dan perspektif yang lugas dan tidak menafikan diri dalam karyanya. Sontak saja perlawanan dan ketidaksepahaman juga datang menghadang. Hingga menimbulkan penilaian dan bahkan pelabelan sebagi sastra selangkangan. Meski ada resistensi politis, arus tak bisa dilawan, beberapa pengarang sampai sekarang ini tetap bergerilya dengan bekalnya ini. Beberapa nama seperti Djenar Maesa Ayu, Andrei Aksana dan yang terbaru saya membaca dari karya Adimodel.
Seksualitas Ala Adimodel
Persoalan seksual dalam sastra yang terbaru ada pada karya Adimodel berjudul Kinky Rain, di samping juga ada persoalan kematian yang juga secara kultural agak tabu juga untuk diperbincangkan. Nuansa seks dan kematian sangat kental sekali terasa dalam 10 cerita dalam buku ini. Seks di sini tampak bukan menjadi suatu bahan untuk mengumbar seksual belaka, di sana seks dianggap sebagi suatu fenomena yang kodrati melekat pada manusia. Seks bukan hanya persatuan dua kelamin dan lain-lainnya untuk sekedar nafsu ataupun fungsi reproduksi. Wacana seks oleh Adimodel dapat dikatakan maju selangkah karena tak hanya memaparkan relasi seksual pertemuan dua kelamin secara normal. Namun di sini bahkan lebih condong pada suatu seks yang terlihat menyimpang dari kacamata konstruksi seksual sosial. Ada fenomena rangsangan seksual, sextoys, incest, kekerasan seksual terhadap anak, sadisme, masokisme, dan yang lebih ekstrem adalah permainan seks dengan memancing kematian dengan imaji-imaji yang menakjubkan.
Seks ibarat magnet. Ia akan menarik yang dekat dengannya melalui rangsangan-rangsangannya. Kadang menjadi suatu dilema, menerima rangsangan malu, tapi menahan juga tak enak. Dalam cerita berjudul ‘’Titik Lingkaran’’ Adimodel mengajarkan suatu kejujuran seks. Cerita mengenai sepasang manusia yang menatap lukisan. Laki-laki di belakang perempuan. Tanpa memandang wajah, hanya dengan suara mereka berdua ereksi. Rangsangan seks sepertinya bukan sesuatu yang harus dinafikan. Ia menawarkan dan patut untuk direspon. Dalam cerita lain berjudul ‘’Kinky Rain’’ sendiri juga terjadi hal seperti itu. Bercerita tentang seorang penangkap cahaya yang bisa saja diartikan sebagai penangkap rangsangan seksual. Setelah menangkap maka hubungan seks mau tak mau harus dilakukan. Hal itu tidak hanya berlaku pada benda hidup, benda replikapun bisa menawarkan sensasi seks, seperti halnya sextoys dalam cerita berjudul ‘’kekasihku meledak’’. Sesuatu yang sebenarnya telah umum dalam variasi seks.
Ada juga fenomena incest yang secara umum diartikan sebagai persetubuhan sedarah adalah salah satu rekam dalam cerita Kinky Rain yang berjudul ‘’Bibir’’. Seorang ayah yang menyetubuhi anaknya merupakan suatu hal yang dianggap sangat biadab di Indonesia. Adimodel mampu memotret hal ini, lebih dulu dari kasus RI yang sekarang ini. Meskipun diiringi dengan kalimat seksual, jelas disini motif utama bukanlah umbaran seks. Ini jelas dengan lugas memperlihatkan kekejian perilaku seks itu sendiri. Salah satu petikan kalimat itu ‘’Setelah tangan itu puas bermandikan basah liurku, iapun mengelus-elus dan memulasi bibirku sambil berkata: jangan bilang ibumu’’.
Kekerasan seks terhadap anak memang bukan lagi menjadi hal yang baru. Anak sebagai sesuatu pihak yang dianggap lemah sering menjadi pelampiasan seksual. Potret ini juga ada di Kinky Rain dengan judul ‘’Van’’. Cerita mengenai anak jalanan yang mengemis di ibukota. Kehidupan yang keras membuatnya mengalami hal-hal yang keras yang tak sepatutnya dia alami. Dia korban dari teman-teman anak jalanan lainnya sebagai lumbung seks. Pengaruh lingkungan memang sangat berpengaruh di sini, dengan tidak adanya yang peduli terhadapnya. Dapat dilihat pada kutipan ini ‘’anak-anak laki-laki yang sedari tadi sudah tidak sabaran dalam hujan mulai mengrubungi Val. Tangan yang mencengkramnya menjadi bertambah banyak. Val menangis. Ia membalas cengkraman-cengkraman itu dengan sebuah tatapan lirih...Jangan terlalu keras seperti kemarin’’.
Wacana seks lain yang mengemuka dalam karya Adimodel adalah seks dengan sadisme dan masokisme. Sadisme merupakan jenis yang puas berhubungan seks dengan menyakiti sedangkan masokisme adalah yang puas dengan disakiti. Model ini dikenal dengan BSDM Bandage and Discipline, Sadism and Masochism. Dapat terlihat pada cerita berjudul ‘’Untie Me’’. Seks telah menjadi sesuatu yang tak dapat diukur lagi dengan logika, maka sudah sepatutnyalah variasi seks untuk diapresiasi. Si wanita yang senang disakiti disini ketagihan untuk disiksa dalam berhubungan seks. Dia pun berkata ‘’Hampir setiap hari ia melecutiku. Menamparku. Memukiliku. Hampir setiap hari dia dia memberikan ras sakit yang luar biasa. Tetapi aku membiarkannya. Aku menikmatinya. Aku bahkan mengundangnya datang’’.
Penyimpangan seksual lainnya dalam cerita Adimodel lebih ekstrim lagi yakni hubungan seksual dengan cara-cara mengundang kematian. Lebih rincinya adalah mencekik dalam bersetubuh. Istilah untuk hal ini adalah Autoerotic Asphixiation. Dalam cerita berjudul ‘’La Petite Mort’’ digambarkan kehidupan sepasang kekasih yang sudah sangat akrab dalam berhubungan seks sehingga menimbulkan satu titik jemu sampai akhirnya menemukan gaya mencekik, baik itu dengan lawan main ataupun dengan properti berupa tali untuk menggantung leher. Sensasi dirasakan pada saat sepertinya nyawa sudah mau melayang kemudian dilepaskan beriringan dengan orgasme. Pertama dalam cerita ini dilakukan dengan sang lelaki mencekik leher kemudian bervariasi sampai berada dikamar mandi. Sang laki bergantung dengan tali dengan tangan diborgol ke belakang dan mata ditup serta mulut disumpal. Penahannya adalah tingklik kecil, sementara perempuan di depannya yang akan menjauhkan tingklik dari kaki ketika mulai dan yang meletakkannya kembali setelah hampir nyawa tercabut dan orgasme. Ada juga dengan menggunakan kantung plastik yang menutup kepala.
Imaji Kematian
Kematian adalah sesuatu yang absurd untuk dieksplorasi mengingat takkan mungkin ada manusia yang bisa menceritakan pengalaman ini. Yang ada hanyalah rekaan dan bayangan subjektif personil. Imajilah yang mencoba bermain melalui perenungan ataupun konteks norma dan agama yang memberi sedikit banyak gambaran. Dalam fiksi, beberapa pengarang telah mencoba me-reka fenomena kematian. Karangan populer dan cerita rekaan lainnya biasanya memberikan gambaran seperti adanya sesuatu khusus menjelang kematian dan adanya malaikat pencabut nyawa, contoh umum malaikat yang memegang senjata pencatuk. Dikarenakan absurd inilah sepertinya sastrawan menemukan suatu keasyikan dalam eksplorasi sketsa-sketsa yang belum terpecahkan ini.
Imaji dalam fenomena sebelum kematian ada dalam judul ‘’La Petite Mort’’. Seperti yang dijelaskan di atas, ini adalah permainan seks dengan kematian. Menjelang kematian terdapat bayangan-bayangan tertentu. Orang yang menjelang kematian tiba di suatu tempat ditemui orang yang telah mendahuluinya dimana biasanya orang itu punya satu kesalahan terhadap yang ditemuinya. Dalam cerita ini dia bertemu Ibunya yang dulu meninggal ditinggal sendiri dan peri kecil yang dulu merupakan benih yang digugurkannya. Karena sering dalam keadaan menjelang kematian, malaikat mautpun pernah berujar padanya untuk jangan bermain-main lagi dengan kematian. Dalam cerita lain berjudul ‘’1441'’ terdapat pula kronologis sang tokoh yang coba bunuh diri dari gedung tinggi, sebelum jatuh dia melihat dan berkomunikasi dengan orang-orang yang pernah disakitinya.
Kematian memang sesuatuyang tak dapat dihindarkan dan tak pernah kita ketahui kapan datangnya. Hal ini menyebabkan kita tanpa ada pilihan dan harus rela menikmati kematian. Namun dalam fiksi hal ini bisa dimodifikasi dengan imajinasi-imajinasi yang bebas dimiliki si penulis. Adimodel pada cerita ‘’Limbo 14'’ menghadirkan sketsa ‘’De Javu’’ kematian. Terdapat delapan cerita dengan keadaan sama dengan versi modifikasi kelanjutan cerita. Sketsa pertama adalah kematian pertama. Lanjut pada yang kedua dengan peristiwa yang sama namun tokoh di dalamnya mempelajari kematian yang pertama meskipun terus saja mati sampai sketsa yang terakhir. Penulis bukanlah bermain, namun tentu saja ada implikasi pesan yaitu tak bisa diubahnya takdir yakni kematian.***
Bayu Agustari Adha,
penulis esai, alumni Sastra Inggris UNP
http://www.riaupos.co/spesial.php?act=full&id=1051&kat=2#.UUaRcXrHrMz
Setelah terbelenggu sekian lama, akhirnya katub-katub itu terbuka juga. Apa yang dianggap patut dan tak patut kerananya sudah terbuka. Menjelmalah sebuah dunia banal di mana titik pasti kebenaran itu bisa dipertanyakan dan diperdebatkan. Tak ada lagi singgasana superioritas yang bebas berkuasa mewacanakan segalanya. Apapun yang coba dikokohkan akan selalu ada titik baliknya dan celah untuk meruntuhkannya. Fenomena ini hampir menjalar ke segala penjuru lintas persoalan. Politik, ideologi, ekonomi, sosial, seni, budaya telah terecoki dalam kenihilan kemapanan.
Hal ini tentunya juga merambah ke sastra sebagai salah satu bidang seni. Berawal dari gerakan poststrukturalist, postmodernist dan post-post lainnya, terbitlah lembaran baru di mana setiap karya berhak merayakan pemikirannya tanpa batas dan dikotomi posisi biner. Apa yang adiluhung, avant garde, aufklarung, sublim dan santun bukanlah menjadi suatu pasak mati dan tolok ukur. Sekarang setiap pengarang telah berhak mengusung setiap pergumulan ideologinya, apakah itu hitam, putih, abu-abu. Kiri, kanan, ataupun poros tengah.
Sastra Indonesia sendiri cukup lama juga terbelenggu dari katub-katub budaya yang mengidentikkan diri dengan ketimuran. Timur yang yang pasif dan menjaga hal-hal yang dikotakkan sebagi tabu. Mengenai masalah tabu ini, seks merupakan hal yang dominan dalam wacananya. Dalam ruang sastra sendiri apabila bergumulan dengan seks, maka itu akan dianggap tidak patut untuk budaya kita yang ‘timur’. Maka apabila ada karya seperti ini akan dicap sebagai karya seronok dan jorok, meskipun setiap manusia ingin melakukannya. Akan tetapi karya itu tetap beredar dan pengarangnya memang harus berani dan rela dicap sebagai pengarang murahan yang hanya pandai mengumbar seksual.
Seiring dengan pengaruh pemikiran segala post-post di atas dan reformasi yang juga patut dianggap sebagai titik tolak, para pengarang Indonesia telah berani membungkus tema seks dengan kedalaman yang lebih dan tak hanya mengumbar seksual, meskipun stigma masyarakat masih menilai dengan sama seperti sebelumnya. Nama Ayu Utami bisa jadi sebagai pionir dalam menawarkan citarasa dengan bumbu seksual dan perspektif yang lugas dan tidak menafikan diri dalam karyanya. Sontak saja perlawanan dan ketidaksepahaman juga datang menghadang. Hingga menimbulkan penilaian dan bahkan pelabelan sebagi sastra selangkangan. Meski ada resistensi politis, arus tak bisa dilawan, beberapa pengarang sampai sekarang ini tetap bergerilya dengan bekalnya ini. Beberapa nama seperti Djenar Maesa Ayu, Andrei Aksana dan yang terbaru saya membaca dari karya Adimodel.
Seksualitas Ala Adimodel
Persoalan seksual dalam sastra yang terbaru ada pada karya Adimodel berjudul Kinky Rain, di samping juga ada persoalan kematian yang juga secara kultural agak tabu juga untuk diperbincangkan. Nuansa seks dan kematian sangat kental sekali terasa dalam 10 cerita dalam buku ini. Seks di sini tampak bukan menjadi suatu bahan untuk mengumbar seksual belaka, di sana seks dianggap sebagi suatu fenomena yang kodrati melekat pada manusia. Seks bukan hanya persatuan dua kelamin dan lain-lainnya untuk sekedar nafsu ataupun fungsi reproduksi. Wacana seks oleh Adimodel dapat dikatakan maju selangkah karena tak hanya memaparkan relasi seksual pertemuan dua kelamin secara normal. Namun di sini bahkan lebih condong pada suatu seks yang terlihat menyimpang dari kacamata konstruksi seksual sosial. Ada fenomena rangsangan seksual, sextoys, incest, kekerasan seksual terhadap anak, sadisme, masokisme, dan yang lebih ekstrem adalah permainan seks dengan memancing kematian dengan imaji-imaji yang menakjubkan.
Seks ibarat magnet. Ia akan menarik yang dekat dengannya melalui rangsangan-rangsangannya. Kadang menjadi suatu dilema, menerima rangsangan malu, tapi menahan juga tak enak. Dalam cerita berjudul ‘’Titik Lingkaran’’ Adimodel mengajarkan suatu kejujuran seks. Cerita mengenai sepasang manusia yang menatap lukisan. Laki-laki di belakang perempuan. Tanpa memandang wajah, hanya dengan suara mereka berdua ereksi. Rangsangan seks sepertinya bukan sesuatu yang harus dinafikan. Ia menawarkan dan patut untuk direspon. Dalam cerita lain berjudul ‘’Kinky Rain’’ sendiri juga terjadi hal seperti itu. Bercerita tentang seorang penangkap cahaya yang bisa saja diartikan sebagai penangkap rangsangan seksual. Setelah menangkap maka hubungan seks mau tak mau harus dilakukan. Hal itu tidak hanya berlaku pada benda hidup, benda replikapun bisa menawarkan sensasi seks, seperti halnya sextoys dalam cerita berjudul ‘’kekasihku meledak’’. Sesuatu yang sebenarnya telah umum dalam variasi seks.
Ada juga fenomena incest yang secara umum diartikan sebagai persetubuhan sedarah adalah salah satu rekam dalam cerita Kinky Rain yang berjudul ‘’Bibir’’. Seorang ayah yang menyetubuhi anaknya merupakan suatu hal yang dianggap sangat biadab di Indonesia. Adimodel mampu memotret hal ini, lebih dulu dari kasus RI yang sekarang ini. Meskipun diiringi dengan kalimat seksual, jelas disini motif utama bukanlah umbaran seks. Ini jelas dengan lugas memperlihatkan kekejian perilaku seks itu sendiri. Salah satu petikan kalimat itu ‘’Setelah tangan itu puas bermandikan basah liurku, iapun mengelus-elus dan memulasi bibirku sambil berkata: jangan bilang ibumu’’.
Kekerasan seks terhadap anak memang bukan lagi menjadi hal yang baru. Anak sebagai sesuatu pihak yang dianggap lemah sering menjadi pelampiasan seksual. Potret ini juga ada di Kinky Rain dengan judul ‘’Van’’. Cerita mengenai anak jalanan yang mengemis di ibukota. Kehidupan yang keras membuatnya mengalami hal-hal yang keras yang tak sepatutnya dia alami. Dia korban dari teman-teman anak jalanan lainnya sebagai lumbung seks. Pengaruh lingkungan memang sangat berpengaruh di sini, dengan tidak adanya yang peduli terhadapnya. Dapat dilihat pada kutipan ini ‘’anak-anak laki-laki yang sedari tadi sudah tidak sabaran dalam hujan mulai mengrubungi Val. Tangan yang mencengkramnya menjadi bertambah banyak. Val menangis. Ia membalas cengkraman-cengkraman itu dengan sebuah tatapan lirih...Jangan terlalu keras seperti kemarin’’.
Wacana seks lain yang mengemuka dalam karya Adimodel adalah seks dengan sadisme dan masokisme. Sadisme merupakan jenis yang puas berhubungan seks dengan menyakiti sedangkan masokisme adalah yang puas dengan disakiti. Model ini dikenal dengan BSDM Bandage and Discipline, Sadism and Masochism. Dapat terlihat pada cerita berjudul ‘’Untie Me’’. Seks telah menjadi sesuatu yang tak dapat diukur lagi dengan logika, maka sudah sepatutnyalah variasi seks untuk diapresiasi. Si wanita yang senang disakiti disini ketagihan untuk disiksa dalam berhubungan seks. Dia pun berkata ‘’Hampir setiap hari ia melecutiku. Menamparku. Memukiliku. Hampir setiap hari dia dia memberikan ras sakit yang luar biasa. Tetapi aku membiarkannya. Aku menikmatinya. Aku bahkan mengundangnya datang’’.
Penyimpangan seksual lainnya dalam cerita Adimodel lebih ekstrim lagi yakni hubungan seksual dengan cara-cara mengundang kematian. Lebih rincinya adalah mencekik dalam bersetubuh. Istilah untuk hal ini adalah Autoerotic Asphixiation. Dalam cerita berjudul ‘’La Petite Mort’’ digambarkan kehidupan sepasang kekasih yang sudah sangat akrab dalam berhubungan seks sehingga menimbulkan satu titik jemu sampai akhirnya menemukan gaya mencekik, baik itu dengan lawan main ataupun dengan properti berupa tali untuk menggantung leher. Sensasi dirasakan pada saat sepertinya nyawa sudah mau melayang kemudian dilepaskan beriringan dengan orgasme. Pertama dalam cerita ini dilakukan dengan sang lelaki mencekik leher kemudian bervariasi sampai berada dikamar mandi. Sang laki bergantung dengan tali dengan tangan diborgol ke belakang dan mata ditup serta mulut disumpal. Penahannya adalah tingklik kecil, sementara perempuan di depannya yang akan menjauhkan tingklik dari kaki ketika mulai dan yang meletakkannya kembali setelah hampir nyawa tercabut dan orgasme. Ada juga dengan menggunakan kantung plastik yang menutup kepala.
Imaji Kematian
Kematian adalah sesuatu yang absurd untuk dieksplorasi mengingat takkan mungkin ada manusia yang bisa menceritakan pengalaman ini. Yang ada hanyalah rekaan dan bayangan subjektif personil. Imajilah yang mencoba bermain melalui perenungan ataupun konteks norma dan agama yang memberi sedikit banyak gambaran. Dalam fiksi, beberapa pengarang telah mencoba me-reka fenomena kematian. Karangan populer dan cerita rekaan lainnya biasanya memberikan gambaran seperti adanya sesuatu khusus menjelang kematian dan adanya malaikat pencabut nyawa, contoh umum malaikat yang memegang senjata pencatuk. Dikarenakan absurd inilah sepertinya sastrawan menemukan suatu keasyikan dalam eksplorasi sketsa-sketsa yang belum terpecahkan ini.
Imaji dalam fenomena sebelum kematian ada dalam judul ‘’La Petite Mort’’. Seperti yang dijelaskan di atas, ini adalah permainan seks dengan kematian. Menjelang kematian terdapat bayangan-bayangan tertentu. Orang yang menjelang kematian tiba di suatu tempat ditemui orang yang telah mendahuluinya dimana biasanya orang itu punya satu kesalahan terhadap yang ditemuinya. Dalam cerita ini dia bertemu Ibunya yang dulu meninggal ditinggal sendiri dan peri kecil yang dulu merupakan benih yang digugurkannya. Karena sering dalam keadaan menjelang kematian, malaikat mautpun pernah berujar padanya untuk jangan bermain-main lagi dengan kematian. Dalam cerita lain berjudul ‘’1441'’ terdapat pula kronologis sang tokoh yang coba bunuh diri dari gedung tinggi, sebelum jatuh dia melihat dan berkomunikasi dengan orang-orang yang pernah disakitinya.
Kematian memang sesuatuyang tak dapat dihindarkan dan tak pernah kita ketahui kapan datangnya. Hal ini menyebabkan kita tanpa ada pilihan dan harus rela menikmati kematian. Namun dalam fiksi hal ini bisa dimodifikasi dengan imajinasi-imajinasi yang bebas dimiliki si penulis. Adimodel pada cerita ‘’Limbo 14'’ menghadirkan sketsa ‘’De Javu’’ kematian. Terdapat delapan cerita dengan keadaan sama dengan versi modifikasi kelanjutan cerita. Sketsa pertama adalah kematian pertama. Lanjut pada yang kedua dengan peristiwa yang sama namun tokoh di dalamnya mempelajari kematian yang pertama meskipun terus saja mati sampai sketsa yang terakhir. Penulis bukanlah bermain, namun tentu saja ada implikasi pesan yaitu tak bisa diubahnya takdir yakni kematian.***
Bayu Agustari Adha,
penulis esai, alumni Sastra Inggris UNP